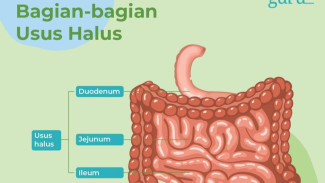Istiqamah Itu Berat, Kisah DN Aidit Membuktikan Hidayah Allah Sangat Mahal
- Istimewa : Press release
Bogor, VIVA Bogor – Malam 30 September 1965, Jakarta seolah membeku. Suasana politik mencekam. Kabar penculikan dan pembunuhan para jenderal Angkatan Darat menyebar cepat. Rakyat dicekam ketakutan, tentara siaga penuh. Dari balik hiruk-pikuk tragedi itu, nama Dipa Nusantara Aidit mencuat sebagai otak pemberontakan.
Namun jarang orang bertanya: siapakah sebenarnya Aidit? Bagaimana mungkin seorang anak ulama yang lahir dari rahim pendidikan Islam, justru mengakhiri hidupnya sebagai tokoh komunis yang mati dalam kesetiaan pada ideologi palu arit?
Santri Kecil yang Cerdas
Nama aslinya Ahmad Aidit. Ia lahir di Belitung, dari ayah seorang ulama terkemuka yang mendirikan sekolah Muhammadiyah di sana. Sang ayah berasal dari Minangkabau, dikenal teguh dalam beragama.
Warga kampung masih mengingat Aidit kecil yang rajin mengaji, suaranya lantang saat adzan menggema tanpa pengeras suara. “Sorot matanya tajam, anak itu pintar sekali. Kalau dia baca Al-Qur’an, semua orang tertegun,” kenang seorang kerabatnya dalam arsip wawancara sejarah.
Ia kerap diminta tampil membacakan ayat suci di berbagai acara keagamaan. Aidit muda adalah simbol harapan keluarga dan kampungnya. Namun, perjalanan hidup kadang berbelok tajam. Semua berubah ketika Aidit remaja berangkat ke Jakarta.
Jalan Berliku: Dari Ahmad Menjadi Aidit
Di ibu kota, Aidit melanjutkan sekolah dagang. Di sanalah pergaulannya mulai bergeser. Buku-buku Marxisme-Leninisme menggantikan kitab-kitab kuning yang dulu ia pelajari. Diskusi aktivis komunis menggantikan halaqah pengajian. Nama “Ahmad” ia buang. Ia memilih menyebut dirinya Dipa Nusantara Aidit, nama yang terdengar modern dan revolusioner.
Kecerdasannya membawanya cepat menanjak dalam hierarki PKI. Ia bolak-balik ke Beijing dan Moskow, menyerap ideologi langsung dari pusatnya. “Aidit lebih condong ke Mao Zedong. Ia mengagumi strategi revolusi RRC,” tulis sejarawan Asvi Warman Adam dalam penelitiannya.
Puncak PKI dan G30S
Di era 1960-an, Aidit bukan sekadar politisi. Ia adalah simbol kebangkitan PKI. Ia duduk sejajar dengan tokoh besar nasional, bahkan dekat dengan Presiden Soekarno.
Namun, Soekarno yang mulai sakit membuat Aidit berpacu dengan waktu. Ia yakin jika Soekarno wafat, PKI akan kehilangan pelindung. Maka ia mendorong percepatan revolusi. Fitnah “Dewan Jenderal” ditiupkan, dan tragedi G30S pun meletus.
Namun Allah menjaga negeri ini. Kudeta itu gagal. PKI runtuh. Dan Aidit berubah status: dari penguasa podium menjadi buronan nomor satu.
Pelarian yang Tragis
2 Oktober 1965, Aidit melarikan diri. Dari Semarang ke Solo, lalu ke Boyolali. Ia berpindah-pindah, bersembunyi di rumah simpatisan. Tentara RPKAD tak pernah berhenti memburunya.
Seorang warga Solo pernah bersaksi: “Aidit itu bersembunyi di lemari. Lemari itu ada pintu rahasianya. Tapi tentara tahu. Waktu dibuka, dia pucat, gemetar. Bukan lagi tokoh besar, hanya seorang pelarian.”
Aidit digelandang ke Boyolali. Pada 23 November 1965, di sebuah sumur tua belakang Batalyon 444, ia dieksekusi mati.
Kata Terakhir yang Mengejutkan
Setiap terpidana biasanya diberi kesempatan berbicara sebelum eksekusi. Harapan orang-orang saat itu: Aidit kembali pada Allah. Mengucap istighfar, shalat taubat, atau setidaknya kalimat syahadat.
Namun Aidit memilih jalan lain. Dengan suara lantang, ia justru berpidato. Ia memuji komunisme, menyerukan agar orang-orang tetap setia pada PKI. Regu tembak yang mendengar muak. Peluru dimuntahkan. Aidit jatuh ke sumur dengan kalimat komunis di bibirnya.
Hilang sudah hafalan Qur’an masa kecilnya. Hilang lantunan adzan yang dulu ia suarakan. Yang tersisa hanya pidato ideologi.
Refleksi: Hidayah Itu Mahal
Kisah Aidit menjadi potret nyata bahwa setiap orang akan mati sesuai kebiasaannya. Ia yang tumbuh sebagai santri, justru wafat dalam kekufuran ideologi.
Hidayah Allah bukan warisan. Ia bukan jaminan bagi anak ulama, bukan pula milik tetap bagi yang pernah rajin mengaji. Ia harus dijaga dengan istiqamah hingga akhir hayat.
Istiqamah itu berat. Ia menuntut lingkungan yang baik, teman shalih yang selalu mengingatkan, serta doa yang tak henti dipanjatkan.
Rasulullah ﷺ mengajarkan doa yang sederhana, namun begitu dalam maknanya:
يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ
“Wahai Yang Membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama-Mu.”
Kisah DN Aidit bukan hanya catatan sejarah kelam 1965, tetapi juga peringatan abadi. Bahwa cahaya hidayah lebih mahal daripada segala kekuasaan. Dan tanpa istiqamah, cahaya itu bisa hilang, meninggalkan seseorang dalam kegelapan yang ia pilih sendiri.